KABARBURSA.COM – Menkomdigi menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ini adalah langkah pertama yang merupakan wujud komitmen yang dimulai dari lingkup internal kementerian.
Isinya adalah pegawai Komdigi wajib menaati dan melaksanakan Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (Online). “Komdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online, diperlukan kolaborasi, sinergi, dan komitmen dengan penuh tanggung jawab dari seluruh sivitas Komdigi,” tegas Meutya Hafid, di Istana Negara, Jakarta Pusat, 1 November 2024 lalu.
Merujuk dana kementerian itu, periode 20 hingga 30 Oktober 2024, Komdigi telah menangani lebih dari 186.187 konten perjudian yang terdeteksi di berbagai platform. Penanganannya mencakup pemblokiran konten, penghapusan akun, dan pemantauan ketat terhadap situs yang memfasilitasi perjudian.
Sepanjang Oktober 2024, Komdigi mencatat sebanyak 325 rekening terindikasi aktivitas perjudian telah diajukan pemblokiran, sementara secara keseluruhan sebanyak 821 rekening bank telah diidentifikasi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Komdigi, Prabu Revolusi, mengungkapkan kolaborasi memberantas judol. Instansinya menggandeng Google dan Meta dari pihak swasta, sedangkan kerja sama intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung, dan perbankan juga ditingkatkan.
“Ini adalah langkah yang terus kami perkuat untuk mengurangi dampak buruk judi online di Indonesia,” ujar Dirjen IKP Komdigi, dikutip laman resminya.
Selain itu, Komdigi membentuk Tim Kerja Penanganan Judi Online pun dibentuk oleh Komdigi, sebagai salah satu program jangka pendek. Menurut data Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika Komdigi mengungkap aktivitas takedown 6.939 konten berdasarkan hasil patroli siber dan aduan masyarakat.
Secara akumulatif sejak 20 Oktober 2024–14 November 2024 pemerintah melakukan takedown sebanyak 290.169 konten judol dengan rincian 268.261 website dan IP, 12.054 konten di Meta, 6.094 file sharing, 2.412 pada Google/YouTube, 1.214 platform X, 74 pada Telegram, dan 38 melalui TikTok.
Di sisi teknis, Komdigi menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempercepat pemblokiran konten, sementara aturan registrasi SIM card baru membatasi maksimal tiga nomor per NIK dan mendorong migrasi ke eSIM untuk mengurangi celah identitas anonim.
Antara 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, pemerintah memutus akses lebih dari 1,3 juta konten judol, terdiri atas 1,192 juta situs dan 127 ribu konten media sosial. Jumlah pemain pun menyusut signifikan, dari sekitar 8,8 juta orang pada 2024 menjadi 3,1 juta orang pada pertengahan 2025, mayoritas dari kelompok berpenghasilan rendah.
Sejumlah langkah nyata rupanya berkontribusi terhadap penurunan transaksi judol. Merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024, total transaksi judol Rp359,81 triliun sepanjang tahun.
Pada kuartal I 2025 nilai transaksi judi daring turun tajam, dari Rp90 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp47 triliun. Jumlah transaksi yang ditekan mencapai 39,8 juta atau lebih dari 80 persen. Nilai deposit judi daring ikut merosot dari Rp15 triliun menjadi Rp6,2 triliun.
Tren penurunan berlanjut ke semester pertama 2025. Nilai transaksi tercatat Rp99,67 triliun, turun 72 persen ytd atau 43 persen dibanding semester I 2024. Jumlah pemain terpangkas hingga tinggal 3,1 juta orang, dengan sekitar 80 persen di antaranya berasal dari rumah tangga berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.
Meski begitu, ancaman tetap nyata. PPATK memperkirakan tanpa intervensi, perputaran uang judi daring di 2025 berpotensi menembus Rp1.200 triliun. Dengan intervensi konsisten, angka itu bisa ditekan hingga sekitar Rp150 triliun, atau lebih optimistis lagi di bawah Rp223 triliun apabila koordinasi lintas sektor berjalan efektif.

Hasil intervensi bukan hanya berupa pemblokiran situs. Sejak Mei 2025, PPATK menempuh langkah lebih radikal dengan memblokir rekening dormant yang dituduh dipakai sebagai sarana deposit judol.
Seperti dirangkum dari berbagai sumber, gelombang pertama PPATK membekukan 28 ribu rekening. Disusul blokir massal terhadap lebih dari 122 juta rekening dormant di 105 bank, yang mengungkap 180 ribu rekening terhubung langsung ke judol dengan nilai transaksi sekitar Rp28 triliun di semester pertama 2025.
Dampaknya langsung terasa. Deposito judol anjlok 55 persen pada Mei 2025, dari Rp5,08 triliun menjadi Rp2,29 triliun, dan kembali turun ke Rp1,5 triliun pada Juni 2025.
Secara agregat, total transaksi judol semester I 2025 tercatat Rp17,5 triliun, jauh lebih rendah dari Rp37,2 triliun pada periode sama 2024.
Permasalahan judol ini semakin krusial lantaran pemainnya cukup mengkhawatirkan, merujuk data PPATK. Data kuartal I 2025, menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 tahun mencapai Rp2,5 triliun. Sebanyak 71,6 persen masyarakat yang melakukan judol berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan memiliki pinjaman di luar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit.
Terbukti, pada tahun 2023 dari total 3,7 juta pemain, 2,4 juta di antaranya memiliki pinjaman tersebut, angka ini naik pada tahun 2024 menjadi 8,8 juta pemain dengan 3,8 juta di antaranya memiliki pinjaman.
Kepala PPATK menyampaikan angka-angka yang ada ini bukan sekedar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judol ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain.
Di saat kementerian digital berjuang merapikan ruang daring, tantangan lain justru datang dari bidang yang lebih mendasar: kesehatan dan ketahanan gizi masyarakat.
Di sinilah perhatian pemerintah beralih ke program sosial berskala besar yang menyentuh langsung dapur rakyat, program MBG, sebuah proyek yang digadang-gadang menjadi warisan utama kabinet baru dalam membangun manusia Indonesia yang sehat dan produktif.
Standar Gizi dan SOP MBG Belum Padu
Program Makan Bergizi Gratis atau disebut MBG sejak awal dijanjikan sebagai investasi gizi nasional untuk anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil. Porsinya diatur untuk memenuhi sekitar 30–35 persen Angka Kecukupan Gizi (AKG) per sajian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui dapur komunitas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam dokumen visi pemerintah, target jangka panjang diarahkan pada sekitar 83 juta penerima pada 2029.
Sayangnya, cita-cita tersebut belum tercapai hingga kini. Pengaturan gizi yang tidak seimbang hingga adanya masalah kesehatan yang menyebabkan penerima manfaat sakit menjadi beberapa contohnya. Padahal, program MBG dijalankan oleh badan khusus yang dibentuk presiden.
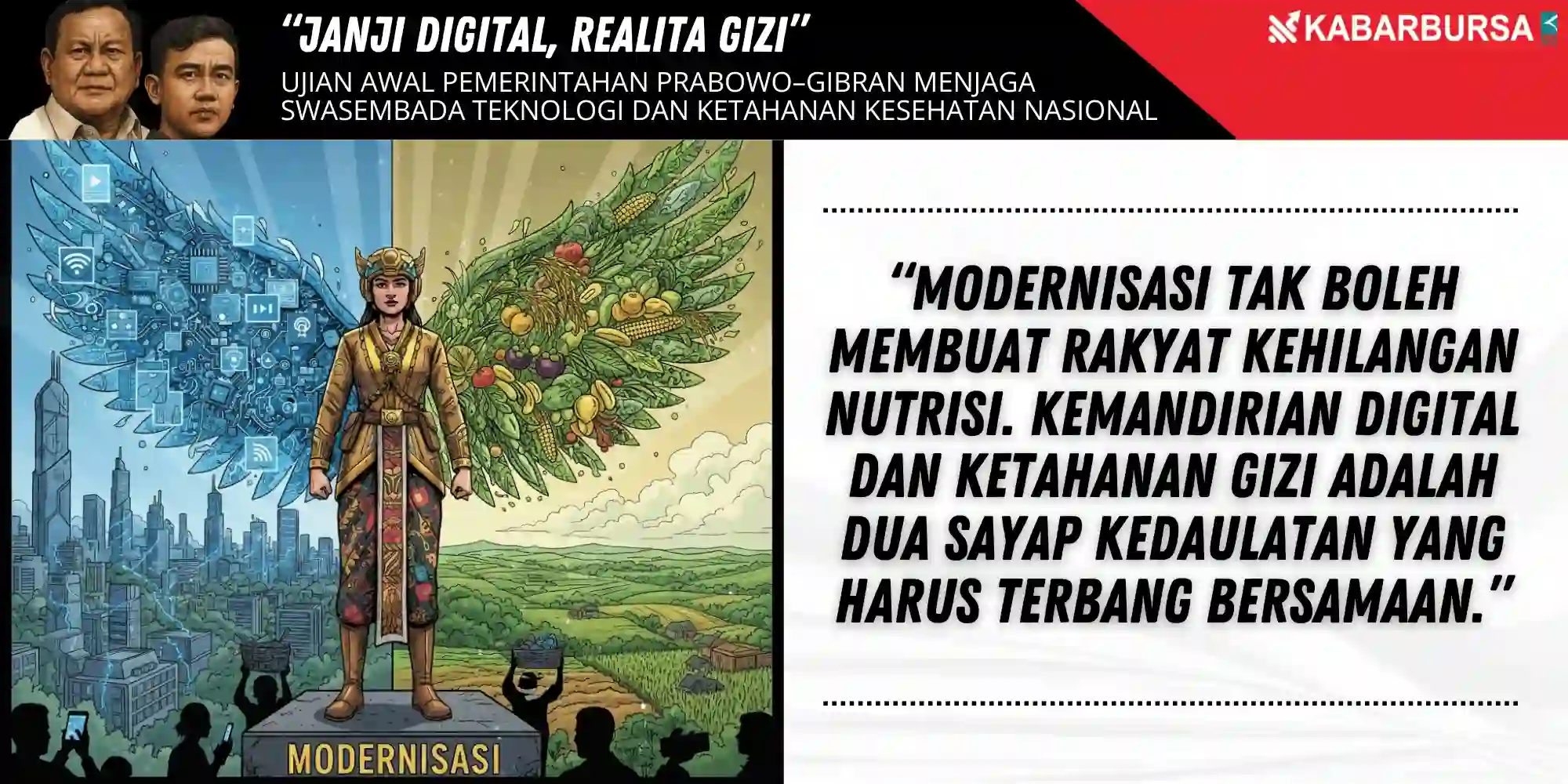
Program MBG dijalankan oleh lembaga baru, yakni Badan Gizi Nasional (BGN). Pembentukannya diatur melalui Perpres 42/2024 tentang Badan Gizi Nasional. Perpres ini memindahkan fungsi yang sebelumnya tersebar di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Sosial (Kemenkes) ke dalam satu badan khusus yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, seperti diatur dalam Perpres 83/2024.
Untuk tahun pertama, 2025, pemerintah merancang anggaran Rp71 triliun. Namun dalam pembahasan berjalan, kebutuhan tambahan hampir Rp100 triliun muncul agar cakupan bisa dipercepat, dengan janji defisit tetap dijaga di bawah tiga persen PDB.
Sebagai konsekuensinya, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, yang memangkas Rp306,69 triliun dari belanja pusat dan daerah, terdiri atas Rp256,1 triliun dari kementerian/lembaga serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Instrumen ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan yang memotong transfer ke daerah (TKD), sementara realokasinya diarahkan untuk menopang MBG sebagai prioritas utama.
Memasuki Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, beban semakin berat. Alokasi MBG diproyeksikan melonjak menjadi sekitar Rp335 triliun atau hampir 10 persen belanja negara.
Dana itu tersebar di berbagai fungsi, dengan porsi terbesar pada pendidikan Rp223,6 triliun, kesehatan Rp24,7 triliun, dan ekonomi Rp19,7 triliun.
Para ekonom memperingatkan, struktur fiskal semacam ini akan menimbulkan trade-off serius, karena program lain terancam terdesak.
Dari sisi target, cakupan MBG diarahkan naik bertahap hingga 82–83 juta penerima pada 2029. Tahap awal dimulai dengan sekitar 570 ribu peserta di 26 provinsi pada Januari 2025, ditargetkan meningkat menjadi 17,5 juta pada pertengahan tahun, sebelum akhirnya diperluas secara nasional.
Selain jumlah peserta, standar gizi ditetapkan agar setiap menu menyumbang sepertiga kebutuhan energi dan protein harian, terutama untuk kelompok anak sekolah dan kelompok rentan.
Implementasi dimulai pada 6 Januari 2025 dengan peluncuran serentak tahap pertama, yang dikerjakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), satuan bentukan BGN. Perkembangan jumlah SPPG menjadi indikator penting. Pada tahap awal Januari 2025, jumlahnya baru mencapai 2.145 unit tersebar di 26 provinsi sebagai basis pilot project.
Sepanjang Januari hingga Juli 2025, program diperluas dengan rencana menjangkau 17,5 juta penerima. Pada 14 Juli 2025, pemerintah mengklaim sudah ada 6,2 juta peserta aktif. Ini sejalan dengan umlah SPPG meningkat tajam menjadi 8.237 unit hingga Juli 2025.
Hanya sebulan kemudian, pada 28 Agustus 2025, capaian diumumkan melonjak menjadi 23 juta penerima. Angka ini memang menegaskan percepatan distribusi, tetapi juga membuka pertanyaan tentang kesiapan kualitas dan tata kelola.
Secara kuantitas, capaian tumbuh sangat cepat. Namun dari sisi mutu gizi, hasilnya jauh dari janji.
Jika dihitung berdasarkan total anggaran MBG 2025 untuk 82,9 juta penerima manfaat, rata-rata biaya per porsi hanya sekitar Rp5.970. Artinya, setiap penerima memperoleh alokasi sekitar Rp1,19 juta per tahun. Angka ini jauh di bawah harga patokan resmi Rp10.000 per porsi yang ditetapkan pemerintah sebagai standar nasional di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian antara desain anggaran dan kebutuhan riil di lapangan.
Sebaliknya, jika harga Rp10.000 per porsi dijadikan acuan, maka total kebutuhan anggaran seharusnya melampaui Rp160 triliun per tahun untuk cakupan penuh. Ketimpangan ini memperkuat kritik sejumlah ekonom bahwa perencanaan fiskal MBG berpotensi overclaim secara politis, namun underfunded secara teknis, karena gap antara target gizi, jumlah penerima, dan alokasi dana tidak berimbang.
Hal tersebut sejalan dengan Kajian Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) pada Januari 2025 mencatat hanya lima dari 29 menu atau sekitar 17 persen yang memenuhi sasaran 30–35 persen AKG, jika melihat angka per porsi.
Bahkan, sekitar 45 persen menu justru menggunakan bahan ultra-processed tinggi gula, yang berpotensi berlawanan dengan misi perbaikan gizi.
Hambatan lain juga bermunculan. Rantai pasok pangan menciptakan tekanan inflasi lokal, meskipun Bank Indonesia (BI) menilai dampaknya masih terkendali. Pemerintah menggerakkan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah untuk menjaga distribusi, namun tetap ada gejolak harga telur, ayam, dan beras di sejumlah wilayah.
Dari sisi keamanan pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan 17 kejadian luar biasa keracunan yang terkait dengan MBG antara 6 Januari hingga 12 Mei 2025 di sepuluh provinsi. Laporan lanjutan menyebut angka itu meningkat menjadi 31 kasus hingga Agustus 2025.
Kasus-kasus ini memaksa BGN memperketat standar operasional. Dari sisi kelembagaan, ekspansi cepat menuntut kapasitas dapur komunitas dan UMKM dalam jumlah besar dengan standar mutu ketat, tetapi organisasi pelaku seperti GAPEMBI baru terbentuk pada September 2025 untuk standarisasi operasional.
Sementara itu, pemerintah mulai menyiapkan digitalisasi tata kelola untuk verifikasi penerima, pemesanan, dan traceability agar celah salah sasaran bisa dipersempit.
Kritik dari pengamat dan analis semakin keras. Temuan CISDI bahwa hanya 17 persen menu memenuhi AKG memperlihatkan gap besar antara desain dan pelaksanaan.
Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan 46 persen publik khawatir program ini tidak efisien dan 37 persen menilai rentan korupsi, dengan potensi kebocoran dana mencapai Rp8,52 triliun per tahun. Kekhawatiran ini diperkuat oleh beban fiskal yang diperkirakan menembus Rp335 triliun pada 2026, atau sekitar sepuluh persen APBN.
CELIOS juga memodelkan risiko defisit jangka panjang bila ekspansi terus dipaksa tanpa perbaikan desain.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahkan merekomendasikan moratorium atau jeda sementara untuk menata ulang standar gizi dan higienitas setelah delapan bulan berjalan, di tengah maraknya insiden keracunan.
Ironisnya, kajian yang sama juga mencatat adanya multiplier effect. PDB naik 0,06 persen, penyerapan tenaga kerja bertambah 0,19 persen, dan upah naik 0,39 persen pada skenario 2025, menegaskan paradoks antara manfaat ekonomi jangka pendek dan risiko kesehatan publik.
Di tingkat operasional, pengawasan BGN mulai diuji di lapangan. Salah satunya insiden di Depok memantik sidak ke SPPG Mampang 1 setelah menu yang beredar, pangsit goreng, kentang rebus, wortel rebus, pisang, dan saus tomat, dipersoalkan publik karena dinilai tidak seimbang gizinya.
Tim Investigasi Independen BGN meninjau kesesuaian menu dengan distribusi di sekolah (6–7 Oktober 2025) dan menyimpulkan pangsit berisi tahu, telur, serta ayam; penggunaan kentang disebut sebagai substitusi untuk menekan food waste yang sebelumnya banyak berasal dari nasi dan sayur.
Hasil peninjauan juga mencatat dapur “cukup layak”, tetapi masih ada kekurangan infrastruktur yang harus disesuaikan dengan Juknis MBG, mulai dari evaluasi menu dan porsi hingga kelengkapan sarana dapur. BGN menegaskan kembali fungsi SPPG sebagai garda mutu: menu wajib aman, higienis, dan memenuhi komposisi gizi bagi penerima manfaat.
Lebih keras dari Depok, langkah penghentian operasional dijatuhkan pada SPPG Kota Soe 1 (NTT) usai KLB keracunan pada 3 Oktober 2025. Nota Dinas 585/D.TWS/10/2025 (6 Oktober 2025) memerintahkan stop serve sampai hasil laboratorium keluar dan perbaikan diterapkan. Dari 3.005 paket soto ayam suwir yang dibagikan, 384 orang terdampak (attack rate 12,81 persen).
Temuan awal mengarah ke kesalahan penanganan bahan, ayam beku sempat disimpan pada suhu ruang, yang meningkatkan risiko kontaminasi. BGN merekomendasikan pelatihan ulang higiene-sanitasi, Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan tightening SOP dapur penyelenggara.
Masalah sertifikasi sendiri memunculkan red flag baru. BGN pada 30 September 2025 menyatakan 198 SPPG telah memegang SLHS (Wilayah I: 102; Wilayah II: 35; Wilayah III: 61). Klaim ini langsung dipertanyakan karena tidak sinkron dengan pernyataan KSP sebelumnya yang menyebut 35 unit saja.
Di saat yang sama, lapisan sertifikasi lain masih tipis: baru 26 SPPG punya HACCP, 15 bersertifikat NKV, 106 memiliki HSP, 23 ISO 22000, 20 ISO 45001, dan 34 bersertifikat halal.
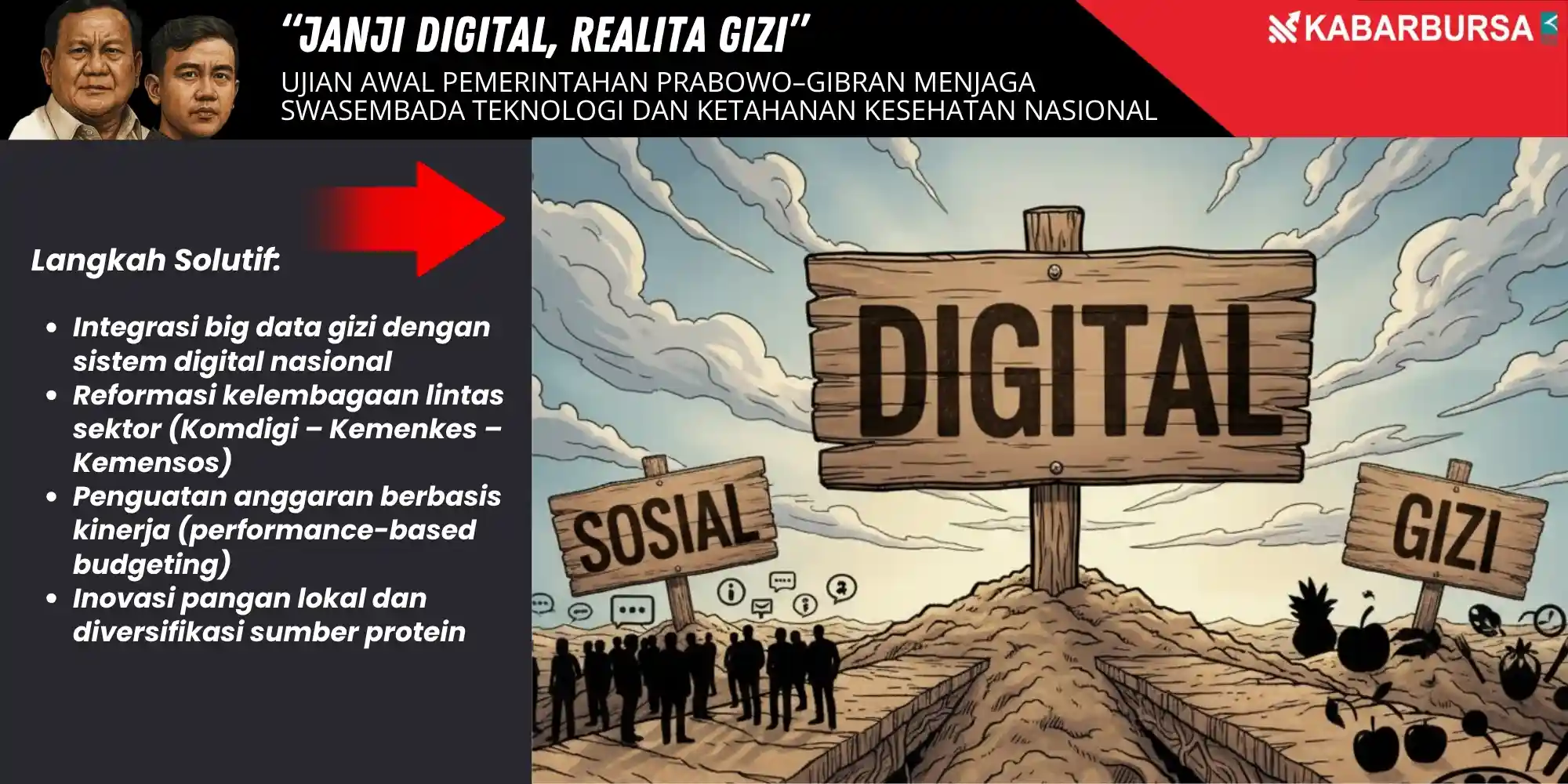
Ketidakterpaduan angka menegaskan dua hal: percepatan administrasi memang terjadi, namun konsistensi data antarlembaga dan kedalaman standar keamanan pangan belum merata. BGN menyatakan terus mendorong percepatan SLHS dan memantau harian, tetapi ekonom menilai capaian ini masih berorientasi administratif, sementara KLB berulang menunjukkan problem struktural yang lebih mendasar.
Nada peringatan juga datang dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP). KSP menekankan perlunya disiplin SOP keamanan pangan. Dalam laporan Senin, 22 September 2025, dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP dan 312 yang benar-benar menjalankannya.
KSP mendorong kewajiban SLHS sebagai prasyarat operasional, integrasi pengawasan puskesmas (10 ribu unit minimal inspeksi bulanan, khusus bulan pertama mingguan), dan sistem pendaftaran terbuka untuk menutup celah pungutan liar.
Target 30.000 SPPG untuk 83 juta penerima menuntut tata kelola yang dapat dieksekusi cepat, termasuk kewenangan stop serve, recall, dan koreksi dalam hitungan jam, bukan hari.
Dari sisi jalur politik-pengawasan, DPR meminta jeda perluasan dapur sampai audit komprehensif rampung.
Wakil Ketua Komisi IX DPR menyarankan model dapur sekolah sebagai SPPG agar pengolahan lebih dekat ke siswa, pengawasan oleh guru-orang tua lebih mudah, dan distribusi massal lintas lokasi, yang kerap memicu risiko makanan basi bisa ditekan.
Skema prasmanan hangat juga diusulkan untuk mengurangi kerentanan cold chain pada produksi skala besar.
Di hilir perlengkapan, rantai pasok food tray menampakkan efek berganda MBG ke manufaktur. PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) melaporkan kontrak berulang melalui yayasan dapur mitra MBG sejak Mei 2025 dengan potensi penjualan Rp40–45 miliar per bulan jika terserap penuh.
Namun, LIVE juga menghadapi banjir produk murah non-SS304 yang mengatasnamakan “304”, cepat rusak, dan berisiko pada keamanan pangan. LIVE menegaskan spesifikasi SS304 sebagai standar MBG, mengedepankan uji pembeda material, sekaligus membantah rumor “pelumas babi”, dinyatakan tidak terdeteksi DNA babi oleh lembaga uji, yang digunakan adalah oli/grease mesin industri, bukan animal fat.
Poin ini menyinggung dimensi lain yakni standardisasi alat makan (food grade, halal, ketahanan pakai) perlu diikat lebih kuat dalam Juknis dan kontrak pengadaan agar tidak jatuh ke perang harga yang mengorbankan mutu.
Adapun sinyal risiko konsumen kian nyata. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membuka posko pengaduan MBG (email, formulir daring, dan tatap muka) untuk mengumpulkan kronologi, bukti, dan memperkuat evaluasi kebijakan.
Data BGN per 25 September 2025 menyebut 5.914 korban dari 70 lokasi KLB. Presiden menyatakan kasus keracunan sebagai “kejadian luar biasa” dan memanggil Kepala BGN sepulang dari tugas luar negeri pada 27 September 2025.
Di lapangan, kesaksian siswa, misalnya kasus nasi goreng beraroma tidak segar di sebuah SMA di Jawa Tengah, menggambarkan masalah dasar freshness, holding time, dan cold/hot chain yang belum stabil.
BGN menyatakan seluruh biaya perawatan pasien KLB MBG ditanggung pemerintah sesuai UU 17/2023 tentang Kesehatan, tetapi publik tetap menunggu tindak lanjut penegakan, termasuk siapa yang bertanggung jawab ketika SOP dilanggar. (*/Selesai)

